Setelah hari kemarin mengiringi keranda yang mengeluarkan bau kesedihan sepanjang jalan, menaburkan kemboja-kemboja mekar ke tanah masih segar, aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku tidak punya lagi siapa-siapa. Daniel mati kelindas truk.
Kematian Daniel memang kemauannya sendiri. Jauh sebelum matanya tertutup abadi, Daniel kerap mengobral pembicaraan seputar kematian kepadaku. Ia bilang mati lebih indah daripada hidup. “Apa buktinya, memangnya kau sudah pernah mati?” kataku dan ia selalu menjawab, “Kelak, ketika aku sudah mati, aku akan mendatangimu lewat mimpi. Akan kukabarkan padamu bahwa apa yang selama ini kukatakan benar adanya.”
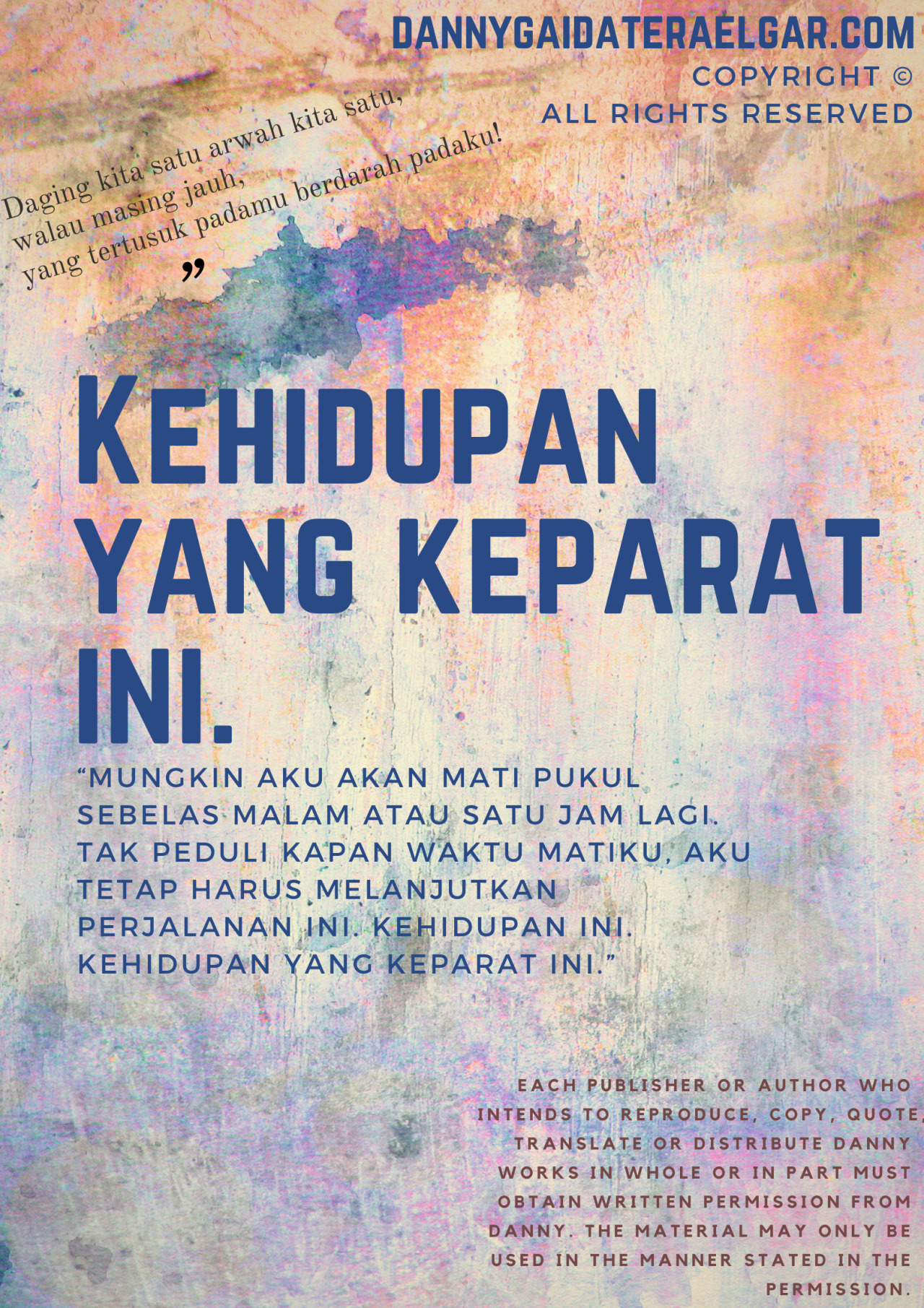
Semalam, hanya beberapa jam setelah jasadnya terbenam dalam ruangan seluas dua kali satu tanpa lampu, Daniel seolah nabi. Ia mengunjungi tidurku hanya untuk membuktikan dirinya benar. Kata-katanya bukan bualan tukang obat. Aku tidak tahu berada di mana diriku saat itu. Daniel menarik tanganku lumayan keras, membuatku nyaris terjatuh. Ia membawaku ke sebuah perbukitan yang penuh rumput-rumput segar dan kambing-kambing berbulu tebal. Kesejukan merambati sekujur tubuh. Aku memang belum pernah mengelilingi dunia, tapi suhu di perbukitan itu suhu ternyaman, tak terlampau panas juga tidak terlalu dingin, yang tak pernah tubuhku rasakan. Saking nyamannya, pikiranku seolah melayang ketika Daniel berdiri di depanku, tegak seperti seorang bapak hendak menyampaikan nasihat kehidupan pada anaknya.
“Aku tidak berbohong padamu, Gustam. Beginilah yang sekarang kurasakan. Kematian memang lebih indah daripada kehidupan,” kata Daniel seraya merentangkan tangan. Wajahnya berbinar-binar. Aku tak pernah melihat ia sesemringah itu. Sebelum sempat aku membalas ucapannya, aku lebih dulu terjatuh dari atas kasur lapuk. Terbangun dari mimpi aneh tersebut. Badanku terasa sakit dan itu artinya aku masih dalam kehidupan. Kehidupan biasa. Kehidupan dengan rasa sakit tak henti-henti.
Pagi pertama tanpa Daniel adalah pagi yang ganjil. Tidak aku temukan seorang lelaki duduk di ruang depan menyilangkan kaki dengan buku di tangan dan secangkir kopi di atas meja. Tidak aku temukan seorang lelaki sependek dadaku yang mengatakan berbagai hal dengan mimik serius seakan-akan akan mengabarkan tentang kiamat. Aku duduk di tempat Daniel biasa duduk. Aku menyeduh kopi dan membaca buku. Melalui jendela, kulihat matahari menggeliat dan pagi mulai tumbuh. Seharusnya aku ceria, seperti segerombol kanak-kanak di luar sana, tetapi aku tidak bisa. Ada kelengangan di sini. Ada yang hilang dan aku tahu itu apa. Ada yang tidak ada dan aku tahu itu memang akan tidak ada selamanya. Menyadari sesuatu hilang dan tidak akan pernah kembali seperti tertusuk pisau sebesar cula badak, begitu menyiksa dan menyesakkan dada.
Pisau? Di dapur ada sebilah pisau yang Daniel rutin asah tiap ia merasa pisau itu sudah menumpul. Pisau itu biasa digunakannya untuk memotong-motong daging, sayuran, dan apa saja. Daniel pandai memasak. Pisau itu tergeletak di wadah kecil berdampingan dengan sendok dan garpu. Bisa saja aku mengambilnya dan menggoreskannya ke pergelangan tanganku. Tapi, itu mustahil. Tiap hal semacam itu terpikir olehku, kelebatan kata-kata Daniel pada suatu masa mengiang di telingaku. “Hidup ini memang keparat. Tapi, membunuh diri sendiri untuk lari dari kehidupan tak kurang keparat dari hidup itu sendiri.”
Lalu kenapa kau pagi itu menyeberangi jalan ramai dan kelewat lengah (ataukah memang sengaja?) sehingga sebuah truk dengan kecepatan setan membuat tubuhmu seperti daging giling, bukankah itu tak beda dengan membunuh diri sendiri dan berarti kau mengkhianati kata-katamu? Kenapa, Daniel, kenapa kau melakukan itu?
“Aku bukan bunuh diri. Aku hanya menemui takdirku sendiri.”
Ah, omong kosong Daniel! Tempo hari kau hampir mati tenggelam di kolam yang kelewat dalam untuk ukuran tubuhmu dan kau menelan pil penghilang sakit kepala dalam porsi berlebih hingga muntah-muntah, lalu aku memarahimu dan mencercamu sedemikian rupa. Apa yang kau katakan? Kau hanya mengatakan, “Aku bukan bunuh diri. Aku hanya menemui takdirku sendiri.” Kau tahu kan Daniel, itu omong kosong belaka? Seperti ucapan para politisi di televisi, sekumpulan kata yang selayaknya dibuang saja ke kakus bersama tahi dan air seni. Begitu juga kata-katamu Daniel. Omong kosong!
Daniel telah pergi, di rumah kontrakan yang aku dan ia sewa susah payah dengan honornya yang tak menentu sebagai penulis koran dan bayaranku sebagai pelukis amatiran yang tak seberapa, yang bisa kulakukan hanya teronggok diam seperti seorang tua yang kelewat renta. Setelah bertahun-tahun kebersamaan sejak peristiwa kebakaran yang memusnahkan keluargaku dan keluarga Daniel, kesendirian serupa nasi basi di tong sampah bagi perut kelaparan. Aku terpaksa melahapnya beserta segala risikonya karena aku tak lagi punya pilihan apa-apa. Karena aku tak lagi punya siapa-siapa.
Di rumah kecil ini, aku dan Daniel pernah menyusun berbagai rencana. Rencana-rencana yang tak akan pernah terwujud. Rencana-rencana yang sudah pecah jadi kenangan dan sejarah.
“Suatu saat nanti kita akan pergi ke Paris. Mampir ke Shakespeare & Co. Kau akan melukis suasana tempat itu dan aku akan menulis satu cerita mengenai tempat itu. Mantap sekali bukan kalau di bawah ceritaku ada titimangsa: Di dekat Shakespeare & Co, Paris, 20XX.”
Daniel mengucapkan itu dengan yakin. Barangkali saja di alam sana ia betul-betul mampir ke Shakespeare & Co. Siapa tahu.
“Aku juga ingin ke komplek pemakaman Novodevichye di Moskow. Kau harus ikut. Aku ingin menziarahi makam Gogol dan terutama Chekhov. Aku berutang banyak padanya, pada Chekhov. Aku banyak belajar menulis cerita darinya, tentang bagaimana menertawakan kehidupan yang keparat ini.”
Mudah-mudahan saja di sana Daniel bisa berjumpa dengan Chekhov. Siapa tahu.
Banyak lagi rencana aku dan Daniel. Namun, di antara tumpukan rencana itu, tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan setelah Daniel ditinggal kekasihnya yang kawin dengan pegawai negeri. Tidak ada perempuan setelah Nadela meninggalkanku tanpa kabar.
Matahari agak meninggi. Tanggal tiga. Sebelum Bu Rosa yang galak itu mengetuk pintu dan menagih uang sewa dengan mata melotot, aku harus mandi dan pergi ke luar. Mandi tak perlu lama-lama. Selain aroma sabun Daniel yang pekat dan mau tak mau menggiring ingatanku kepadanya, aku juga mesti berlomba dengan Bu Rosa yang barangkali sedang bercermin sebentar untuk kemudian berdiri di depan pintu rumah.
Untunglah, Bu Rosa belum muncul. Dengan langkah-langkah panjang, aku berjalan menjauhi rumahku dan rumah Bu Rosa yang persis di samping kanan rumahku. Kutarik topiku ke bawah, menghindari silau mentari sekaligus tatapan Bu Rosa yang bisa saja memanggilku tiba-tiba.
Tak sampai lima menit, aku sudah tiba di pinggir jalan raya. Jalan raya tempat malaikat maut mencabut nyawa Daniel. Di tengah jalan itu, samar merah darah masih tampak. Kering dan agak menghitam. Aku seolah melihat kematian di situ. Aku seolah melihat Daniel ketika ruhnya teregang. Aku seolah melihat sebuah truk melindas lelaki pendek yang gampang saja membuat sopir truk mana pun terluput melihatnya. Aku seolah melihat itu semua dan kematian serasa terpampang di pelupuk mata.
Mungkin aku akan mati pukul sebelas malam atau satu jam lagi, tak peduli kapan waktu matiku, aku tetap harus melanjutkan perjalanan ini. Kehidupan ini. Kehidupan yang keparat ini. Mungkin aku akan mati keracunan atau ditabrak lari atau kena peluru nyasar, tak peduli bagaimana cara matiku, aku tetap harus melanjutkan perjalanan ini. Kehidupan ini. Kehidupan yang keparat ini.
Aku melangkah, menyeberang, menengadah ke langit. Cerah. Tak kulihat apa-apa selain lengang langit. Tak kudengar apa-apa selain derap langkahku sendiri. Entah pada langkah keberapa, aku limbung, pandanganku berkunang-kunang. Mungkin aku keracunan makanan seminggu lalu atau sebuah truk menabrakku atau seorang polisi mengiraku maling dan menembakku. Aku tidak tahu. Samar-samar suara Bu Rosa terdengar, memanggil namaku dan perihal tunggakan kontrakan selama tiga bulan. Samar-samar di kejauhan sana kulihat Daniel tersenyum di atas perbukitan dengan rumput-rumput segar dan kambing-kambing berbulu tebal. Semuanya samar, lalu sepenuhnya pudar.
Daging kita satu arwah kita satu,
walau masing jauh,
yang tertusuk padamu berdarah padaku!




